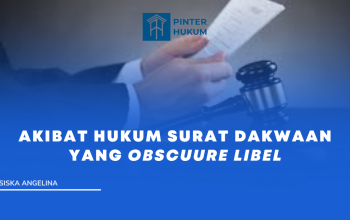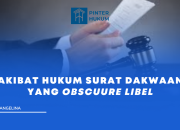Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya juga memiliki sistem hukum yang pluralistik. Selain hukum nasional yang berlaku secara umum, masyarakat adat di berbagai daerah masih menjunjung tinggi hukum adat sebagai pedoman hidup mereka.
Dalam praktiknya, kerap terjadi ketegangan antara hukum adat dan hukum negara, terutama ketika keduanya memiliki pandangan berbeda terhadap suatu peristiwa hukum. Salah satu kasus nyata adalah perusakan hutan adat milik masyarakat Dayak di Kalimantan oleh perusahaan sawit yang mendapat izin dari negara (PT Sawit Mandiri Lestari).
Perusakan Hutan Adat oleh Perusahaan Sawit
Beberapa tahun terakhir, masyarakat adat di Kalimantan Tengah, khususnya suku Dayak Tomun, menghadapi permasalahan serius akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Salah satu kasus yang cukup disoroti terjadi pada tahun 2022, ketika sebuah perusahaan sawit merambah kawasan hutan yang oleh masyarakat adat dianggap sebagai hutan keramat (tanah ulayat). PT Sawit Mandiri Lestari (SML) tersebut mengklaim telah mendapatkan izin konsesi dari pemerintah daerah.
Namun, masyarakat adat menolak kehadiran perusahaan tersebut karena kawasan yang dibuka adalah wilayah sakral yang memiliki nilai spiritual dan historis yang tinggi. Akibat pembukaan lahan tersebut, terjadi kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta terganggunya keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Masyarakat kemudian melakukan protes, upacara adat tolak bala, dan menuntut penghentian kegiatan perusahaan. Namun, karena secara hukum formal perusahaan memiliki izin yang sah, tuntutan masyarakat tidak mendapat dukungan dari aparat penegak hukum.
Dalam teori hukum adat, khususnya Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Lalu menurut Ter Haar, hukum adat bersifat konkret, kasuistis, dan hidup dalam masyarakat. Artinya, keberlakuan hukum adat sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat setempat.
Dalam konteks masyarakat adat suku tomun, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup relasi spiritual antara manusia dan alam. Oleh karena itu, tanah dan hutan adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan keberlangsungan komunitas adat. Sistem penguasaan tanah dalam hukum adat tidak bersifat individual, melainkan komunal.
Tanah ulayat tidak bisa diperjualbelikan atau dialihkan tanpa persetujuan komunitas adat. Pemberian izin konsesi kepada perusahaan tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum adat tersebut. Teori “hak ulayat” yang dijelaskan oleh Hazairin juga menegaskan bahwa tanah ulayat adalah hak kolektif masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh negara, sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Kasus ini juga menunjukkan adanya konflik antara “legalitas” dan “legitimasi”. Izin perusahaan mungkin sah secara hukum formal (legal), namun tidak sah secara sosial dan adat (tidak legitimate). Dalam teori hukum adat, tindakan yang tidak mendapatkan restu masyarakat adat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum di mata komunitas tersebut.
Peran Negara dan Perlindungan terhadap Hukum Adat
Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari ketentuan tersebut masih sangat lemah. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya pengakuan hukum formal terhadap banyak komunitas adat. Selain itu, mekanisme konsultasi publik yang diwajibkan dalam proses perizinan sering kali hanya menjadi formalitas.
Baca juga: Tradisi Potong Jari di Papua, Tinjauan dalam Hukum Adat
Teori rekognisi dalam hukum adat menyatakan bahwa hukum adat baru akan memiliki kekuatan formal apabila diakui oleh negara. Namun, pengakuan ini seharusnya tidak menjadikan hukum adat sebagai subordinat dari hukum negara, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang harus dipertimbangkan secara setara. Dalam hal ini, peran lembaga adat sebagai penjaga nilai-nilai lokal perlu diperkuat, bukan dilemahkan oleh proses hukum yang sentralistik.
Penutup
Kasus perusakan hutan adat di Kalimantan mencerminkan belum harmonisnya hubungan antara hukum adat dan hukum negara. Ketegangan ini berakar dari perbedaan pandangan mengenai tanah, sumber daya alam, dan pembangunan.
Diperlukan pendekatan hukum yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal serta mekanisme perlindungan yang nyata bagi masyarakat adat agar hukum adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga tetap hidup dan dihormati dalam praktik bernegara.